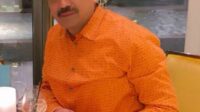Oleh: Dr. Hendra Dinatha, S.H., M.H.*)
Pendahuluan: PPP dalam Persimpangan Sejarah
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah manifestasi dari upaya konsolidasi politik umat Islam Indonesia pada awal Orde Baru. Lahir pada tahun 1973 dari fusi empat partai Islam – Nahdlatul Ulama (NU), Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), dan Parmusi – PPP sejak awal diposisikan sebagai “rumah besar umat Islam”. Konsolidasi ini tidak hanya bersifat politis, tetapi juga ideologis, karena dimaksudkan untuk memperkuat representasi politik Islam di tengah sistem politik yang direkayasa oleh negara melalui penyederhanaan partai.
Kejayaan PPP dapat dilihat dalam kiprahnya selama beberapa dekade. Pada masa Orde Baru, meskipun mengalami tekanan politik dan represi dari rezim, PPP tetap mampu menjadi wadah aspirasi politik Islam. Dukungan kuat dari jaringan pesantren, kyai kampung, dan ormas Islam menjadikan PPP simbol perlawanan kultural terhadap hegemoni negara. Bahkan, hingga awal era Reformasi, PPP masih mampu mempertahankan identitasnya sebagai salah satu partai besar dengan basis massa yang relatif solid. Namun demikian, dinamika politik pasca- reformasi memperlihatkan adanya fragmentasi suara umat Islam ke berbagai partai lain, termasuk partai-partai Islam baru maupun partai nasionalis yang merangkul isu-isu keislaman.
Ironinya, Pemilu 2024 menjadi titik nadir bagi PPP. Untuk pertama kalinya sejak berdiri, PPP gagal menembus ambang batas parlemen dan kehilangan kursi di Senayan. Fenomena ini mencerminkan krisis ganda: krisis identitas dan krisis kepemimpinan. Identitas politik Islam yang dahulu menjadi basis legitimasi PPP seolah memudar di tengah perebutan isu keagamaan oleh partai-partai lain. Sementara itu, kepemimpinan PPP dinilai tidak mampu mengartikulasikan narasi baru yang relevan dengan kebutuhan umat Islam kontemporer, khususnya kalangan muda dan kelas menengah Muslim.
Dalam perspektif teori kelembagaan politik (neo-institutionalism), kegagalan PPP menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan politik dan sosial dapat dipahami sebagai ketidakmampuan melakukan adaptasi institusional (Hall, P. A., & Taylor, R. C. R. (1996)). PPP tetap bergantung pada struktur lama yang berbasis patronase tradisional tanpa inovasi signifikan dalam strategi komunikasi politik maupun kaderisasi. Padahal, partai politik yang ingin bertahan harus mampu mentransformasikan diri sesuai konteks zaman, baik dalam aspek ideologi maupun praksis politik.
Oleh karena itu, posisi PPP saat ini berada pada persimpangan sejarah. Di satu sisi, ia masih memiliki modal simbolik sebagai partai Islam tertua yang mewarisi tradisi perjuangan politik umat. Di sisi lain, jika tidak segera melakukan reorientasi dan regenerasi kepemimpinan, PPP berisiko menjadi sekadar catatan sejarah politik Islam Indonesia. Dalam konteks inilah, figur ulama intelektual seperti Prof. KH Husnan Bey Fananie muncul sebagai sosok yang berpotensi mengembalikan arah perjuangan PPP ke kiblat politik umat Islam, melalui rekonsolidasi basis tradisional dan modern, termasuk pemuda Islam di pesantren dan alumni- alumninya.
Figur Ulama-Intelektual sebagai Jawaban
Krisis identitas dan kepemimpinan yang tengah dialami PPP tidak dapat diselesaikan hanya dengan retorika elektoral semata. Partai ini membutuhkan sosok yang memiliki otoritas moral sebagai ulama, kapasitas intelektual sebagai akademisi, serta legitimasi kultural yang berakar pada tradisi umat. Dalam teori kepemimpinan politik, seorang pemimpin partai yang sukses tidak hanya ditentukan oleh kemampuan manajerial, tetapi juga oleh apa yang disebut Max Weber (1978) sebagai “otoritas karismatik”, yakni legitimasi yang tumbuh dari pengakuan masyarakat terhadap integritas dan keunikan kepemimpinan seseorang. Dalam konteks PPP, figur semacam ini dapat menjadi jembatan antara tradisi dan modernitas, antara basis konstituen klasik dan kebutuhan transformasi kontemporer.
Prof. KH Husnan Bey Fananie hadir sebagai representasi nyata dari model kepemimpinan tersebut. Sebagai seorang ulama, ia tidak tercerabut dari akar tradisional pesantren dan kultur keislaman Indonesia. Sebagai akademisi, ia menempuh jalur keilmuan hingga meraih gelar profesor dengan reputasi internasional. Sebagai diplomat, pengalamannya menjadi Duta Besar RI di Azerbaijan menambah dimensi global pada profilnya, sehingga ia memahami dinamika geopolitik dan peran Islam Indonesia dalam percaturan dunia. Dan sebagai pemimpin ormas Islam, ia kini menjabat Ketua Umum PP Parmusi, yang membawanya dekat dengan jaringan kyai kampung maupun pemuda Islam di basis akar rumput.
Di tengah meningkatnya pragmatisme politik, keberadaan seorang pemimpin yang memiliki legitimasi moral dan intelektual menjadi kian penting. Demokrasi Indonesia pasca- reformasi memang membuka ruang yang luas bagi partisipasi politik, namun di sisi lain juga melahirkan politik transaksional dan oligarkis. Partai-partai Islam pun tidak luput dari jebakan ini, seringkali terjebak pada logika pragmatisme tanpa menawarkan narasi besar yang menginspirasi umat. Dalam kondisi seperti itu, kehadiran Husnan Bey dapat menjadi koreksi, dengan menghadirkan politik yang bernuansa religius, etis, dan berorientasi pada pembangunan peradaban, bukan sekadar perebutan kursi kekuasaan.
Jika dianalisis dengan pendekatan ekologi politik, keberhasilan suatu partai Islam dalam mengartikulasikan aspirasi umat sangat ditentukan oleh kemampuannya membaca dinamika sosial, ekonomi, dan kultural masyarakat. Husnan Bey Fananie memiliki keunggulan dalam hal ini karena tidak hanya memahami aspirasi tradisional umat (pesantren, kyai kampung, ormas Islam), tetapi juga menguasai diskursus global terkait modernitas, digitalisasi, dan
geopolitik Islam. Posisi hibrid ini menjadikannya relevan bagi generasi muda Islam yang membutuhkan identitas kuat namun tetap kompatibel dengan tantangan zaman.
Lebih jauh, Husnan Bey memiliki visi untuk membangun kader-kader politisi berkarakter religius-nasionalis. Di tengah politik elektoral yang kian pragmatis, regenerasi kader yang berintegritas menjadi masalah serius. PPP kerap dikritik karena gagal menyiapkan kaderisasi yang mampu tampil sebagai tokoh nasional yang visioner. Dengan latar belakang akademisi dan pengalaman global, Husnan Bey dapat mengubah wajah PPP menjadi partai yang serius membina kader, bukan sekadar mengelola mesin elektoral jangka pendek.
Dari perspektif teori keadilan John Rawls (1999), politik harus dijalankan dalam kerangka fairness, yakni keadilan sebagai dasar kontrak sosial. Visi Husnan Bey yang menekankan pentingnya etika, karakter, dan integritas dapat menjadi modal untuk mengembalikan PPP ke jalur politik yang lebih adil dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat, bukan hanya kepentingan elit. Dengan kata lain, kepemimpinan ulama-intelektual seperti dirinya dapat menghidupkan kembali semangat idealisme dalam politik Islam yang selama ini meredup.
Selain itu, legitimasi kultural Husnan Bey bersifat inklusif. Ia bukan figur yang hanya dekat dengan elit pesantren besar atau tokoh politik tertentu, tetapi juga dikenal mampu merangkul kyai kampung, pemuda Islam di pesantren-pesantren daerah, serta alumni pesantren yang kini berkiprah di berbagai sektor. Dengan jaringan yang demikian luas, ia berpotensi menyatukan kembali “empat arus besar” yang dahulu melahirkan PPP – NU, Perti, PSII, dan Parmusi – dalam spirit kebangkitan politik Islam yang moderat, nasionalis, dan berakar kuat di masyarakat.
Oleh karena itu, sosok Prof. KH Husnan Bey Fananie dapat dipandang sebagai jawaban strategis bagi PPP yang kini berada di persimpangan jalan. Ia memiliki kombinasi unik: otoritas moral, kapasitas intelektual, pengalaman internasional, serta legitimasi kultural yang membumi. Dalam kerangka inilah, PPP dapat menemukan momentum kebangkitan baru jika mampu menempatkan figur ulama-intelektual ini sebagai poros kepemimpinan.
Merangkul Kembali Empat Unsur Pendiri PPP
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) lahir dari penyatuan empat unsur besar politik Islam: NU, Perti, PSII, dan Parmusi. Formasi ini merupakan hasil politik penyederhanaan Orde Baru, namun juga menyimpan makna historis: adanya ikhtiar menyatukan kekuatan politik Islam di bawah satu atap. Seiring perjalanan waktu, ikatan itu kian longgar, bahkan tercerai- berai oleh kepentingan praktis dan pergeseran kepemimpinan. Kehilangan kursi di Senayan pada Pemilu 2024 memperlihatkan bahwa PPP tidak hanya mengalami krisis elektoral, tetapi juga kehilangan koneksi organik dengan basis-basis tradisional yang dulu menopangnya. Dalam konteks ini, upaya merangkul kembali empat unsur pendiri PPP menjadi agenda strategis yang tak bisa ditawar.
Prof. KH Husnan Bey Fananie memiliki modal sosial, kultural, dan intelektual untuk mengembalikan orientasi PPP kepada basis tradisionalnya. Dengan latar belakang Parmusi, ia membawa identitas historis yang kuat, namun sekaligus memiliki kedekatan dengan NU, Perti, dan PSII melalui jejaring pesantren, ormas Islam, dan keterlibatannya dalam wacana kebangsaan. Kemampuannya menjembatani tradisi dan modernitas, kampung dan kota, pesantren dan dunia akademik, membuatnya berpotensi menjadi figur integratif yang mampu mengonsolidasikan kembali empat pilar historis PPP.
Dalam perspektif neo-institusionalisme, keberhasilan sebuah partai politik tidak hanya ditentukan oleh struktur formal, tetapi juga oleh kemampuan menghidupkan kembali norma, nilai, dan identitas kolektif yang menjadi dasar legitimasi. PPP, dengan warisan empat partai Islam, memiliki reservoir identitas yang kaya. Namun, reservoir itu kini tak lagi otomatis bekerja sebagai modal elektoral. Dibutuhkan figur yang mampu mengaktifkan kembali ingatan kolektif tersebut dan menjadikannya energi politik yang relevan. Husnan Bey, sebagai ulama- intelektual, memiliki kapasitas untuk menjalankan fungsi ini.
Kekuatan utama PPP pada masa lalu adalah basis ulama, baik yang berakar di perkotaan maupun di pedesaan. Kyai kampung memainkan peran penting sebagai mediator politik di tingkat akar rumput, sekaligus penjaga otoritas moral yang mengikat umat dengan partai. Namun, selama dua dekade terakhir, hubungan organik ini kian terputus. PPP sering kali lebih sibuk dengan intrik elite ketimbang merawat jaringan kyai di akar rumput. Dalam kondisi ini, kepemimpinan Husnan Bey yang akrab dengan dunia pesantren dan kyai kampung dapat merekatkan kembali hubungan yang renggang tersebut.
Tidak kalah penting adalah peran ulama perkotaan dan intelektual Muslim modernis yang juga menjadi bagian dari tradisi PPP. PSII dan Parmusi, misalnya, memiliki basis kuat pada kalangan modernis, akademisi, dan aktivis perkotaan. Selama ini, relasi antara ulama kampung dan ulama perkotaan seringkali terjebak dalam dikotomi, padahal keduanya bisa saling melengkapi. Figur Husnan Bey, yang sekaligus seorang akademisi dan ulama, dapat menjembatani gap ini. Ia bisa mengartikulasikan visi Islam kultural yang membumi di pedesaan sekaligus wacana Islam modernis yang resonan di perkotaan.
Dari perspektif ekologi politik, rekonsolidasi PPP harus melibatkan jaringan pesantren dan alumni sebagai modal sosial yang sangat besar. Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga sebagai pusat kaderisasi sosial, politik, dan budaya. Alumni pesantren yang kini tersebar di berbagai sektor kehidupan dapat menjadi agen mobilisasi baru bagi PPP. Namun, untuk itu dibutuhkan kepemimpinan yang diakui oleh komunitas pesantren, dan Husnan Bey memiliki legitimasi tersebut.
Lebih jauh, rekonsolidasi empat unsur pendiri PPP di bawah figur ulama-intelektual memiliki signifikansi politis yang lebih luas. Dalam teori identitas politik, keberhasilan suatu partai untuk bertahan bukan hanya bergantung pada strategi elektoral jangka pendek, tetapi juga pada kemampuannya mempertahankan identitas ideologis yang membedakannya dari partai lain. PPP selama ini sering terjebak menjadi sekadar “partai Islam pragmatis” yang
tidak memiliki diferensiasi signifikan dari partai-partai lain. Dengan mengembalikan orientasi pada empat unsur pendiri, PPP berpeluang memulihkan identitas ideologisnya sebagai rumah besar umat Islam.
Konsolidasi ini tentu tidak mudah. Tantangan datang dari fragmentasi internal, kompetisi dengan partai Islam lain, serta logika politik elektoral yang semakin transaksional. Namun, solusi tidak mungkin ditemukan tanpa keberanian mengambil langkah strategis. Dengan figur seperti Husnan Bey, yang memiliki integritas moral, pengalaman global, dan akar tradisional yang kuat, peluang itu tetap terbuka. PPP harus mampu menjadikan rekonsolidasi ini bukan sekadar romantisme sejarah, melainkan sebagai peta jalan untuk membangun kembali kepercayaan umat Islam.
Akhirnya, merangkul kembali NU, Perti, PSII, dan Parmusi bukan sekadar agenda elektoral, tetapi juga agenda peradaban. Dengan modal ulama, pesantren, alumni, dan tradisi intelektual Islam, PPP bisa kembali menjadi partai yang bukan hanya merebut kursi kekuasaan, tetapi juga membangun etika politik baru yang religius, inklusif, dan berkeadilan. Dalam kerangka inilah, Prof. KH Husnan Bey Fananie dapat dipandang sebagai figur kunci yang mampu mengembalikan PPP pada jati dirinya dan menjadikannya relevan bagi Indonesia menuju 2045.
Pemuda Islam sebagai Energi Kebangkitan
Kebangkitan kembali PPP tidak dapat dilepaskan dari keterlibatannya dengan generasi muda Islam. Dalam konteks demokrasi kontemporer, pemuda adalah motor penggerak perubahan sosial-politik. Mereka bukan hanya pemilih potensial, tetapi juga produsen wacana, aktivis sosial, dan aktor digital yang menguasai ruang publik baru. Prof. KH Husnan Bey Fananie menegaskan bahwa pemuda Islam ideal adalah mereka yang progresif, proaktif, kreatif, inovatif, dan futuristik. Dengan kerangka tersebut, ia melihat pemuda sebagai energi strategis yang dapat mengembalikan PPP ke posisinya sebagai partai politik umat yang relevan.
Dari sudut pandang teori demografi politik, Indonesia tengah menikmati bonus demografi, di mana lebih dari 60% penduduk berada pada usia produktif. Dalam pemilu 2024, suara pemilih muda (milenial dan Gen Z) mencapai lebih dari separuh jumlah pemilih. Jika PPP gagal memanfaatkan potensi ini, maka partai akan semakin terpinggirkan. Sebaliknya, jika PPP mampu mengartikulasikan aspirasi dan identitas pemuda Islam dengan baik, ia bisa mengembalikan posisinya sebagai salah satu kekuatan utama dalam politik nasional. Figur seperti Husnan Bey, dengan reputasi intelektual dan kedekatan kultural dengan pesantren, memiliki kapasitas untuk memimpin strategi ini.
Namun, tantangan besar terletak pada bagaimana menghubungkan tradisi Islam dengan aspirasi modern pemuda. Generasi muda kini hidup dalam dunia digital, global, dan sangat cepat berubah. Sementara itu, tradisi pesantren menekankan nilai moral, kedisiplinan, serta keterikatan pada ulama. Di sinilah relevansi Husnan Bey terlihat. Dengan latar belakang akademik dan pengalaman internasional, ia dapat merumuskan format baru keterlibatan
pemuda Islam dalam politik: tetap berakar pada tradisi, tetapi terbuka terhadap inovasi dan tantangan global.
Pesantren memiliki peran strategis sebagai laboratorium kader pemuda Islam. Sejarah membuktikan bahwa pesantren telah melahirkan tokoh-tokoh penting bangsa, mulai dari pejuang kemerdekaan hingga intelektual dan politisi kontemporer. Dengan lebih dari 30 ribu pesantren di seluruh Indonesia, basis ini adalah modal sosial yang luar biasa besar. Jika diorganisasi dengan baik, pesantren dapat kembali menjadi sumber kaderisasi pemuda yang religius, nasionalis, dan ideologis. Husnan Bey, dengan posisinya sebagai ulama-intelektual, bisa menghubungkan PPP dengan ekosistem pesantren yang selama ini semakin renggang.
Dalam kerangka teori modal sosial Robert Putnam (2000), keberhasilan suatu organisasi politik tidak hanya ditentukan oleh struktur formal, tetapi juga oleh jaringan kepercayaan, norma, dan nilai yang ada di masyarakat. Pesantren dan alumni-alumninya menyimpan modal sosial yang dapat diaktifkan untuk membangun kembali PPP. Melalui jaringan ini, partai tidak sekadar menawarkan janji elektoral, tetapi juga membangun ikatan emosional dan ideologis dengan pemuda Islam.
Keterlibatan pemuda Islam juga penting untuk mengatasi krisis ideologi dalam politik kontemporer. Demokrasi Indonesia pasca-reformasi seringkali ditandai oleh pragmatisme dan transaksionalisme, yang membuat politik kehilangan visi besar. Pemuda Islam dapat menjadi motor perlawanan terhadap tren ini, dengan menghadirkan politik yang berorientasi pada etika, nilai, dan idealisme. Husnan Bey menekankan perlunya membangun kader yang berkarakter religius-nasionalis, yang tidak hanya mengejar kekuasaan, tetapi juga menjadikan politik sebagai sarana ibadah dan pengabdian pada bangsa.
Di era digital, pemuda juga berperan sebagai aktor kultural yang menguasai media sosial, ruang diskursus publik, dan teknologi informasi. PPP selama ini dikenal lambat beradaptasi dengan politik digital. Dengan visi futuristik Husnan Bey, PPP berpeluang untuk membangun basis digital di kalangan santri, mahasiswa, dan pemuda Muslim. Jika strategi ini dijalankan, PPP dapat menjelma sebagai partai Islam yang tidak hanya berakar di kampung dan pesantren, tetapi juga hadir kuat di ruang publik digital yang menentukan arah politik masa depan.
Dengan demikian, pemuda Islam bukan hanya sekadar bonus demografi, tetapi juga energi kebangkitan yang dapat mengembalikan PPP ke jalur sejarahnya. Namun, energi ini hanya bisa dimanfaatkan jika partai memiliki kepemimpinan yang kredibel, berakar pada tradisi, dan melek tantangan global. Figur Prof. KH Husnan Bey Fananie memenuhi kriteria tersebut: seorang ulama-intelektual yang dapat menjembatani tradisi dengan modernitas, serta menggerakkan pemuda Islam untuk membangun politik yang etis, visioner, dan berkeadilan.
Mengembalikan Kiblat Politik Umat Islam
Sejarah politik Indonesia membuktikan bahwa umat Islam selalu memainkan peran sentral dalam pembentukan arah bangsa. Namun, dalam dua dekade terakhir, politik Islam di Indonesia mengalami fragmentasi akibat dominasi politik pragmatis yang melunturkan basis ideologis. Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang sejak kelahirannya pada 1973 dimaksudkan sebagai “rumah besar umat Islam”, kini justru terjebak dalam krisis representasi, ditandai dengan kegagalannya menembus ambang batas parlemen pada Pemilu 2024 (Haris, 2024). Fenomena ini menunjukkan perlunya reposisi PPP agar dapat kembali menjadi pilihan utama umat Islam, bukan sekadar aktor minor dalam sistem multipartai yang cair.
Reposisi PPP hanya dapat dicapai jika partai ini menegaskan kembali posisinya sebagai partai ideologis yang berbasis pada nilai-nilai Islam dan nasionalisme, bukan partai pragmatis yang sekadar mengejar kursi kekuasaan. Menurut teori partai politik ideologis, kekuatan utama partai bukan pada kemampuan manuver politik sesaat, melainkan pada konsistensi dalam memperjuangkan nilai dan identitas yang berakar pada basis sosialnya (Panebianco, 1988). Dalam hal ini, PPP perlu mengartikulasikan kembali Islam sebagai sumber etika politik dan panduan moral bagi demokrasi Indonesia.
Prof. KH Husnan Bey Fananie muncul sebagai figur yang potensial untuk mengembalikan arah tersebut. Sebagai ulama intelektual sekaligus akademisi dengan pengalaman diplomasi, Husnan memiliki keunggulan ganda: otoritas moral dan kapasitas modern. Hal ini penting karena umat Islam, khususnya generasi muda, membutuhkan model kepemimpinan politik yang tidak hanya religius tetapi juga rasional dan visioner. Dalam perspektif Weberian, legitimasi kepemimpinan modern menuntut kombinasi antara kharisma, tradisi, dan rasionalitas hukum (Weber, 1978). Husnan Bey memiliki modal ini secara relatif lengkap, sehingga ia bisa menjadi titik konsolidasi umat.
Dalam konteks politik praktis, kembalinya PPP sebagai kiblat politik umat Islam membutuhkan strategi rekonsolidasi basis. Pertama, PPP harus kembali merangkul pesantren dan kyai kampung yang selama ini menjadi jangkar tradisional Islam Indonesia. Kedua, PPP harus membangun komunikasi intensif dengan ormas Islam dan organisasi kepemudaan, sehingga energi bonus demografi dapat disalurkan secara produktif. Ketiga, PPP harus menyusun platform politik yang jelas terkait isu-isu strategis bangsa: reforma agraria, pemerataan pembangunan, keadilan sosial, pemberantasan korupsi dan kedaulatan ekonomi. Dengan demikian, PPP bukan hanya tampak religius secara simbolik, tetapi juga substantif dalam advokasi kebijakan publik.
Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Rawls tentang “keadilan sebagai fairness”, di mana partai politik seharusnya tidak hanya memperjuangkan kepentingan mayoritas atau elite, tetapi menjamin keadilan bagi kelompok yang paling rentan (Rawls, 1999). Jika PPP di bawah Husnan Bey mampu mengartikulasikan Islam dalam kerangka keadilan sosial yang inklusif, maka partai ini bisa menjadi kekuatan moral sekaligus politik yang relevan. Islam tidak hanya hadir sebagai simbol, melainkan juga sebagai energi transformasi sosial yang nyata.
Lebih jauh, tantangan menuju Visi Indonesia Emas 2045 menuntut kehadiran partai- partai dengan orientasi ideologis yang jelas. Dalam kerangka pembangunan jangka panjang, PPP dapat berkontribusi dengan mengartikulasikan gagasan pembangunan yang berbasis pada etika Islam: keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan bersama (maqashid al-syari‘ah). PPP bisa menjadi penyeimbang di tengah dominasi oligarki partai besar yang cenderung pragmatis dan teknokratis. Dengan basis sejarahnya sebagai partai Islam tertua pasca-fusi, PPP memiliki legitimasi untuk mengklaim posisi strategis ini.
Husnan Bey dapat memanfaatkan modal kultural dan intelektualnya untuk memimpin proses transformasi ini. Melalui kaderisasi politik berbasis pesantren, ia bisa mencetak politisi muda yang tidak hanya mengejar kekuasaan, tetapi juga memiliki etika religius dan semangat kebangsaan. Strategi ini tidak hanya mengembalikan PPP sebagai rumah besar umat Islam, tetapi juga menjadikannya sebagai sekolah politik yang membentuk elite bangsa yang berkarakter.
Jika reposisi ideologis ini berhasil, maka PPP akan mampu mengembalikan kiblat politik umat Islam di Indonesia. Partai ini akan kembali menjadi pusat gravitasi politik Islam yang inklusif, progresif, dan relevan dengan tantangan abad ke-21. Dengan kepemimpinan Husnan Bey Fananie, PPP bukan hanya mengulang kejayaan masa lalu, tetapi menorehkan babak baru sebagai partai Islam modern yang berkontribusi nyata dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Penutup: PPP dan Jalan Kebangkitan Baru
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kini berada di persimpangan sejarah yang menentukan. Krisis identitas yang berujung pada absennya PPP di Senayan pasca Pemilu 2024 memperlihatkan bahwa strategi politik pragmatis tanpa fondasi ideologis tidak lagi relevan. Umat Islam, yang dulu menjadikan PPP sebagai “rumah besar”, kini menuntut adanya reposisi yang mengembalikan marwah partai sebagai representasi politik Islam yang autentik. Dalam konteks inilah, figur Prof. KH Husnan Bey Fananie tampil sebagai simbol rekonsiliasi antara tradisi keulamaan dan modernitas intelektual.
Husnan Bey bukan hanya seorang ulama, tetapi juga seorang akademisi yang menguasai wacana global. Perpaduan ini memberinya modal unik untuk menjembatani kebutuhan umat Islam yang mengakar pada pesantren dan kyai kampung dengan tantangan era digital, geopolitik, dan bonus demografi. Dalam perspektif kepemimpinan transformasional, figur seperti Husnan berpotensi menciptakan perubahan bukan hanya di level organisasi, tetapi juga dalam horizon nilai dan orientasi partai. Ia bukan sekadar pemimpin administratif, melainkan agen perubahan.
Bagi PPP, kepemimpinan Husnan Bey dapat menjadi jawaban bagi krisis representasi yang selama ini membelit. Dengan basis moral keulamaan, ia memiliki legitimasi kultural yang kuat di hadapan umat. Dengan kapasitas intelektual, ia mampu mengartikulasikan gagasan PPP dalam bahasa politik modern yang bisa diterima generasi muda. Dan dengan pengalaman
diplomasi, ia punya wawasan strategis dalam membangun positioning PPP sebagai partai nasionalis-religius yang relevan di level global. Inilah kombinasi yang jarang dimiliki oleh figur lain.
Harapan umat Islam terhadap PPP tidak hanya sebatas nostalgia sejarah, tetapi juga merupakan kebutuhan aktual dalam lanskap demokrasi Indonesia. Dalam situasi di mana partai-partai besar kerap terjebak dalam oligarki dan politik transaksional, umat Islam membutuhkan alternatif yang lebih ideologis, bermoral, dan berorientasi pada keadilan sosial. Jika PPP gagal menjawab kebutuhan ini, maka kebangkitannya hanya akan menjadi wacana kosong tanpa substansi.
Momentum Muktamar 2025 menjadi titik krusial dalam perjalanan PPP. Ia bukan sekadar forum rutin pemilihan ketua umum, melainkan arena menentukan arah ideologis partai ke depan. Pilihan terhadap figur pemimpin tidak lagi semata soal siapa yang mampu memenangkan kursi kekuasaan, tetapi siapa yang mampu mengembalikan PPP pada khitahnya sebagai rumah politik umat Islam. Dalam kerangka teori institusionalisme baru (March & Olsen, 1989), keputusan dalam Muktamar ini akan membentuk norma, identitas, dan orientasi PPP dalam jangka panjang.
Jika Husnan Bey diberi mandat, PPP berpeluang untuk membangun jalan kebangkitan baru. Rekonsolidasi dengan kyai kampung, jaringan pesantren, dan ormas Islam bisa menjadi basis akar rumput yang kokoh. Sementara visi pembangunan bangsa yang religius-nasionalis bisa menarik simpati pemuda Islam, yang kini menjadi bonus demografi. Strategi ini bukan hanya mengembalikan PPP ke panggung politik nasional, tetapi juga memastikan bahwa politik Islam hadir sebagai kekuatan konstruktif dalam membangun Indonesia menuju 2045.
Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan para pemilik saham politik PPP: para muktamirin yang akan menentukan arah partai pada September 2025 mendatang. Mereka dihadapkan pada pilihan historis: apakah akan melanjutkan pola lama yang pragmatis, ataukah berani melakukan reposisi ideologis melalui kepemimpinan baru. Pilihan ini bukan hanya menentukan nasib PPP, tetapi juga menentukan arah politik Islam di Indonesia secara keseluruhan.
Dalam logika sejarah, partai politik yang gagal membaca momentum transformasi biasanya akan tersingkir dari panggung. Tetapi partai yang mampu menjawab kebutuhan zaman dengan figur dan gagasan yang tepat akan menemukan kebangkitannya kembali. PPP memiliki modal sejarah, basis kultural, dan simbol religius yang kuat. Kini yang dibutuhkan hanyalah kepemimpinan yang mampu menyatukan modal-modal tersebut dalam kerangka kebangkitan baru.
Oleh karena itu, Muktamar 2025 bukan hanya peristiwa organisatoris, tetapi momentum sejarah yang akan menentukan apakah PPP mampu kembali tegak sebagai kiblat politik umat Islam. Jika benar langkah diambil, PPP dapat kembali menjadi partai ideologis yang progresif, kontributif, dan relevan dalam mewarnai perjalanan demokrasi Indonesia menuju Indonesia
Emas 2045. Figur Husnan Bey Fananie, dengan kapasitasnya sebagai ulama-intelektual, adalah simbol harapan bagi terwujudnya jalan kebangkitan baru itu.
*)Dr. Hendra Dinatha, S.H., M.H., Ketua Bidang Polhukam PP PARMUSI, Waketum PP GMPI dan juga sebagai Wakil Rektor Universitas Jayabaya, Jakarta.